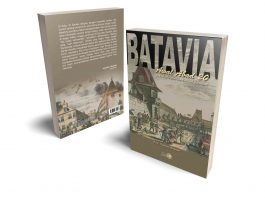Jakarta Sejarah 400 Tahun, Jakarta, Masup Jakarta 2011, penulis: Susan Blackburn, tebal: 392 hlm + xxiv, penerbit: Masup Jakarta, dan terbitan: Pertama dalam bahasa Indonesia 2011
Buku sejarah panjang Jakarta (1619-1985) ini pernah dicekal Pemerintah Orde Baru (Orba) pada 1987. Sebab dianggap nyinyir pada sejumlah pejabat ditambah lagi menawarkan perspektif ‘kaya melawan miskin’ pada isi kupasannya. Kekiri-kirian kira-kira demikianlah.
Namun, sebagai studi sejarah sosial pertumbuhan kota dan perubahan gaya hidup Indonesia, buku ini acuan klasik. Kekayaan sumbernya dan ilustrasi, menempatkan buku ini terlengkap sejak Oud Batavia karya F de Haan (1935). Susan Blackburn berargumen Jakarta punya sejarah kompleks, enerjik sekaligus paradoksal. Ketika masih bernama Batavia, ia adalah kristalisasi interaksi antara Belanda dengan masyarakat asli dan warga peranakan Cina. Deskripsi pembentukan identitas Jakarta itu begitu menginspirasi meskipun mesti diberi catatan-catatan.
Baca Juga:
- Jakarta 1970-an Kenangan Sebagai Dosen
- Jakarta 1960-an Kenangan Semasa Mahasiswa
- Jakarta 1950 Kenangan Semasa Remaja
Sebut saja aspek fisik kota dan kemajemukan penduduk. Ini sudah menggejala di kota-kota tradisional di Pantura Jawa, seperti Tuban dan Banten. Termasuk Sunda Kelapa yang jadi cikal bakal Jakarta. Jadi model benteng, kanal dan aspek urban sebenarnya sudah ada sebelum Batavia. Sistem perkampungan berdasar etnis/agama/pekerjaan juga bukan inovasi Belanda karena sudah dikenal dibanyak tempat Indonesia bagian barat sebelum abad ke-17. Belanda justru mencontoh dan meneruskan karakter kosmopolitan khas itu. Aroma kolonial hanya memberi dinamika baru di atas aura lama kehidupan akulturatifnya.
Sejak 1619, ketika simbol kekuasaan Pangeran Jayakarta diluluhlantakkan, kota ini mulai diarahkan oleh segelintir orang Belanda sebagai kota perusahaan VOC. Batavia disematkan mimpi-mimpi elite yang berkonsekuensi pada ambiguitas dan paradoks kota ini selama 320 tahun kemudian. Benar kalau Blackburn beranggapan sejak awal kota ini dibangun berkonsep eksklusif. Sesudah kemerdekaan, ‘topeng kepura-puraan’ warisan kolonial ini masih dilanjutkan dalam konteks pertarungan konstan tiap penguasanya. Mereka yang memimpin kota selalu menjadi fokus dan faktor penentu bagi arah sejarah kota ini.
Jakarta adalah konsep pembangunan Indonesia baru, apapun yang berbau kolonial, meski baik, diganti. Pusat kota dan pusat pemerintahan dipindahkan. Nilai-nilai kolonial yang berseberangan ditinggalkan. Di atas Batavia dibuat label baru: Jakarta. Dalam konteks inilah harus dilihat perdebatan 22 Juni sebagai hari lahir Jakarta yang dimulai pada 1950-an.
Presiden Sukarno dan kemudian Gubernur Ali Sadikin berusaha memotong ikatan emosional Jakarta dengan sejarahnya. Mereka memilihkan jalan baru yang ‘modern’ dengan ide perombakan dalam kerangka pembangunan nasional. Selama masa awal Republik, dalam sekejap Sukarno ingin menjadikan Jakarta kota modern. Ia memaksa Ratu dari Timur bereinkarnasi dalam bentuk yang berbeda dari nasibnya, mengemban imaji yang dianggap lebih cocok bagi sebuah ibukota kebanggaan. Jakarta harus jadi tempat yang sejajar dengan kota-kota internasional lain, seperti Manila dan Singapura.
Adalah Ali Sadikin yang bertanggungjawab menjadikan Jakarta kota metropolitan, meski berbagai cara dihalalkan, termasuk penggusuran kampung-kampung dan menjadikan sebagian besar penduduknya bak anak tiri. Jakarta adalah cermin politik, kiblat perubahan dan harus menjadi pusat Indonesia terpenting.
Selain peran sentral elite, perubahan politik dan tingginya arus migrasi menambah perspektif Jakarta yang kacau dan salah arah. Arus besar migrasi dan budaya urban kian memenuhi Jakarta dengan gengsi yang menjauhkan karakter asli. Identitas Jakarta kabur. Lenyap rohnya Jakarta. Tiada tersisa kampung-kampung unik nostalgik ‘tempo doeloe’.
Alergi terhadap konsep ‘kemiskinan’ ditandai berlipatgandanya bangunan perumahan dan kantor beton-beton tanpa jiwa, atau mal-mal seragam yang miskin kreativitas. Warna lokal tergerus dan kian termarjinalkan ke pinggiran. Persoalan ekologi yang akut—ruang terbuka yang diskriminatif, masalah perumahan, polusi, banjir, nyamuk, air bersih dll—jadi lingkaran setan permasalahan yang historis. Iklan-iklan pariwisata tentang Jakarta terkini masih memamerkan visi penguasa yang bermimpi ke depan dan merepresentasikannya yang modern untuk dunia internasional. Persetan kaum miskin kota serta identitas sejarah.
Dalam aspek lain, penerbit buku ini seperti merancang penerbitannya sebagai sambungan dari karya Jean G. Taylor yang lebih dulu diterbitkan, Kehidupan Sosial di Batavia. Taylor mengupas peran perempuan dalam sejarah budaya dan pembentukan masyarakat urban nan kompleks dan unik, suatu konsolidasi budaya asli, Cina, Arab maupun Eropa sepanjang abad ke-17–19. Blackburn menegaskan pada abad ke-20, perempuan kian berperan sebagai perantara budaya ketika tingkat migrasi melamban dan interaksi mereka makin terjalin.
Akhirnya, inilah buku yang memukau. Ia punya kekuatan otoritatif bagi siapa saja yang ingin cepat mengenal Jakarta. Bukan hanya kekhasannya, tapi juga persoalan-persoalannya. Sayang memang buku ini berhenti sampai 1985, dan karena itu Jakarta pun agak kurang beruntung untuk punya “buku pegangan komplit”. Namun kekurangan sedikit atas fenomena mega urban bersatunya Jakarta dengan sekeliling sejak Reformasi yang tidak tercakup harusnya jadi pemicu pengamat untuk melengkapinya.
Kompleksitas dan tantangan baru seperempat abad terakhir jelas menentukan arah Jakarta ke depan, namun bagaimanapun bentuk studi baru tentang Jakarta, buku ini tak mungkin diabaikan sebab ia menawarkan pengetahuan sejarah yang holistik yang mampu memberikan masukan inspiratif bagaimana kesinambungan serta perubahan itu tetap mencirikan kota paradoks ini.
Buku Jakarta Sejarah 400 Tahun karya Susan Blackburn bisa didapatkan di di Tokopedia, BukaLapak, dan Shopee atau telpon ke 081385430505.