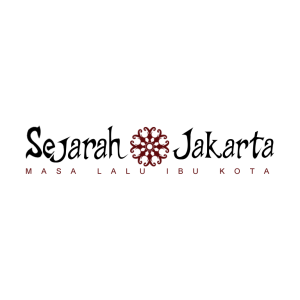Ondel-ondel bukan sekadar boneka raksasa alat hiburan belaka. Tetapi, medium kultural tumbuhnya whistleblowing attitude alias budaya sedia berani mengusir segala kekuatan jahat.
Salah besar jika menganggap ondel-ondel sekadar boneka raksasa. Di balik tampang seram dan kemayu serta badan tambun sepasang ondel-ondel terdapat kearifan tradisi untuk menjungjung hidup bersih dari kejahatan yang merusak kehidupan bersama.
Ondel-ondel yang marak terlihat saban ulang tahun Jakarta sudah dikenal selama berabad-abad sebagai bagian tradisi masyarakat aslinya. Hidup di kampung-kampung Betawi agraris pinggiran. Masuk kota hanya pada saat-saat pesta rakyat, seperti tahun baru Belanda dan Cina alias Sin Tjia.
Sambutan gembira dan persenan uang dihaturkan kepada arak-arakan ondel-ondel yang dianggap simbol pembawa dan pejaga harapan-harapan dijauhkan dari tangan jahat keburukan tak bermoral. Namun, semua berobah pada 1954, Walikota Sudiro menganggap tradisi itu tak pantas, merendahkan pribumi, seraya mengeluarkan larangan.
Setelah lebih 30 tahun, datanglah Gubernur Ali Sadikin. Ia bukan saja menghidupkan kembali ondel-ondel yang sudah terpojok itu, malahan menjadikannya ikon Jakarta. Ali tak paham dunia Betawi, namun dalam memoarnya Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977, ia mengaku tergetar pesan Sukarno bahwa kosmopolitan bukan sekadar “physical face yang wardig” atau wajah penampilan yang berharga, tetapi juga identitas kultural.
Saat itulah, Ali menemukan pada budaya Betawi basis kultural yang mampu mendukung Jakarta menjadi kosmopolitan sekaligus ibukota negara kepulauan terbesar. Dalam konteks itu ondel-ondel adalah salahsatu yang terpenting. Mengapa?
Ali menjadi gubernur dengan mewarisi persoalan bestuursvoering alias pelaksanaan pemerintahan yang tengah dijangkiti kebobrokan tata susila dan akhlak. Selain defisit keuangan, terjadi rupa-rupa korupsi yang disebutnya imoralitas. Kenyataan buruk ini bukan saja terjadi dalam pemerintahan tingkat lokal, tetapi juga nasional.
Setiap waktu dirasa Ali imoralitas itu semakin membesar sebab korupsi yang semakin permisif. Ali pun segera ikut dalam barisan Mohammad Hatta yang pada akhir 1960-an terang-terangan menyatakan: “Korupsi telah menjadi kebudayaan Indonesia”.
Baca Juga:
- Si Biang Kerok Benyamin S
- Abdul Chaer Ahli Linguistik Asli Betawi, Raih Penghargaan Seni dan Budaya
- Sabeni Jago Tanah Abang dan Etik Silat Betawi
Untuk memperbaikinya, Ali pun mengikuti saran Hatta. Ia mereformasi birokrasi dan menambahkannya dengan mencari media pentakbiran nilai etik anti kejahatan moral yang sudah menyejarah serta diakrabi wujud manifestasinya oleh masyarakat Jakarta. Saat itulah ondel-ondel menjadi penting sebab merupakan simbolisasi budaya anti kekuatan dan perbuatan jahat, busuk tak bermoral sebagaimana yang menjadi asal kata korupsi itu, corruptus atau perbuatan buruk, busuk tak bermoral. Sejarah memang menunjukkan, meskipun ada banyak versi sejarah ondel-ondel, namun semua mengarah pada satu kesimpulan bahwa ondel-ondel lahir dan tumbuh dari suatu riwayat panjang hasrat-hasrat terkuat untuk mengingatkan pentingnya terus memerangi laku yang merusak kehidupan masyarakat.
Keberadaan dan tempat ondel-ondel sebagai simbol anti kekuatan jahat semakin kokoh di masyarakat Jakarta dengan kehadiran bangsa Tionghoa yang juga punya tradisi mengarak boneka raksasa. Hanya saja, ironisnya, ondel-ondel tinggal boneka hiburan belaka yang terlupakan makna kehadirannya sebagai medium kultural tumbuhnya whistleblowing attitude alias budaya sedia berani mengusir segala kekuatan jahat yang akan mendorong kehidupan bersama masuk lobang bencana. Rupanya Ali Sadikin sudah keburu purna tugas dan tidak punya penerus sebelum akhirnya ondel-ondel yang sengaja dihadirkan pada hampir setiap kantor Pemerintah DKI Jakarta dan banyak tempat di ibukota itu dikenali arti kehadirannya yang azali itu. Akibatnya di Jakarta korupsi sudah seperti – pinjam lagu legendaris “ngarak ondel-ondel” dari 1970-an karya Benyamin S– “kepale anak ondel-ondel yang ditaroin puntungan, nyale bekobaran”.
Ondel-ondel akhirnya adalah kisah material culture yang alasan keberadaanya terlupakan sebagai counter culture atas korupsi yang kata Hatta sudah membudaya itu. Mungkin ini bukan kehilangan yang berarti, tetapi seperti kata pakar korupsi Syed Hussain Alatas saat iblis pembela korupsi (defentio diabolica) telah memenuhi atmosfir kehidupan, maka seluruh kekuatan penentangnya harus dikumpulkan, kehilangan kekuatan itu yang sangat kecil sekalipun adalah suatu kekalahan besar.
Pernah dimuat di majalah TEMPO, 20 Juni 2011.