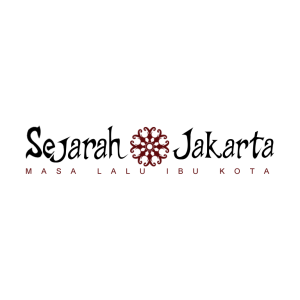Inilah pertama kalinya Pramoedya menggambarkan priyayi sebagai warga berengsek di masyarakat. Selanjutnya, dengan melakukan hal itu dia mengedepankan kenyataan bahwa gaya hidup priyayi hanya dapat dipertahankan dengan mengeksploitasi orang-orang yang kurang beruntung.
Pada Desember 1955 ketika “Machluk Dibelakang Rumah” (MDR) yang dibukukan dalam Tjerita dari Djakarta ditulis, Pramoedya mampu menggambarkan para pembantu rumah tangga secara lebih mendalam dan lebih simpatik.
Sementara dalam cerita lain di bukunya itu, “Djongos…”, Pramoedya memperhatikan bahwa para pembantu rumah tangga memiliki beberapa tingkat perhambaan, dengan tokohnya Sobi dan Inah, sebagai yang terendah dan terburuk dari mereka semua.
Sementara itu, di “MDR” kualitas para pelayan tidak begitu bergantung pada kualitas layanan yang mereka berikan kepada juragan mereka dan lebih banyak kepada kualitas juragan tersebut.
Jadi, narator cerita mengamati bahwa mereka yang bekerja untuk keluarga Tionghoa terlihat bersih dan memiliki ekspresi wajah yang sama dengan majikan mereka. Mereka yang bekerja untuk orang Eropa sangat patuh dan mereka yang bekerja untuk priyayi Jakarta terlihat tidak terawat karena terlalu banyak bekerja dan kurang gizi (MDR: 119).
Baca Juga:
- Si Biang Kerok Benyamin S
- Abdul Chaer Ahli Linguistik Asli Betawi, Raih Penghargaan Seni dan Budaya
- Jakarta 1970-an Kenangan Menjadi Dosen
Seorang pelayan yang bekerja untuk seorang priyayi tertentu diketahui mengenakan pakaian yang sama sepanjang waktu dia bekerja di tempat itu. Dia bekerja selama 12 jam sehari dengan imbalan satu kali makan ditambah dengan sisa-sisa makanan.
Pelayan lainnya tidak menerima gaji, tetapi sebagai imbalannya dia disekolahkan. Namun, karena dia memiliki wajah yang menyenangkan, majikan perempuannya merasa terancam olehnya dan memutuskan untuk memecatnya. Majikan perempuannya itu berpendapat bahwa pendidikan tidak akan menjamin masa depan yang lebih baik dan lebih cerah.
Pramoedya melalui narator menyatakan bahwa banyak dari para majikan itu sendiri sebelumnya adalah pembantu rumah tangga ketika mereka pertama kali tiba di ibu kota (MDR: 121). Mereka telah melupakan penderitaannya dan kenyataan bahwa mereka adalah majikan yang paling sering memperlakukan pelayan mereka secara tidak pantas.
Majikan lainnya yang sudah menjadi bagian dari kelas priyayi sebelum mereka pindah dari daerah bersikeras dengan segala cara mempertahankan gaya hidup mereka. Mereka menolak melakukan pekerjaan kasar macam apa pun. Penolakan mereka untuk bekerja kasar berlanjut karena mereka mampu memeras tenaga para pelayan mereka.

Dalam mengamati para majikan priyayi tersebut, Pramoedya juga melihat perbedaan antara mereka dan orang lain dari kelas sosial yang berbeda. Para petani pintar yang dapat mengendalikan panen dapat meningkatkan kekayaan mereka. Begitu pula para pedagang dan pengusaha yang datang untuk hidup di kota.
Mereka meningkatkan status sosial dan ekonomi serta dapat hidup seperti raja. Bahkan para pekerja perkotaan mulai menyadari kekuatan potensial mereka dan bergabung ke dalam kelompok yang patut diperhitungkan. Hanya priyayi yang ketinggalan zaman. Mereka bersikeras untuk hidup dalam kemegahan masa sebelum Republik Indonesia hadir, masa yang ditopang oleh perbudakan para pelayan mereka.
Inilah pertama kalinya Pramoedya menggambarkan priyayi sebagai warga berengsek di masyarakat. Selanjutnya, dengan melakukan hal itu dia mengedepankan kenyataan bahwa gaya hidup priyayi hanya dapat dipertahankan dengan mengeksploitasi orang-orang yang kurang beruntung.
Pada saat yang sama, Pramoedya menantang keabsahan citra harmonis kontrak sosial “gusti-kawula” yang menjadi acuan dalam tradisi Jawa—tentang ikatan “gusti-kawula” dalam tradisi Jawa, baca, S. Moertono State and Statecraft in Old Java (Ithaca, Cornell Modern Indonesian Project, 1963)—dengan mengalihkan simpatinya dari priyayi ke masyarakat pekerja kasar. Dia juga melihat pemandangan sosial kontemporer, dimana para pekerja kasar adalah anggota masyarakat yang kurang beruntung.
Dalam penggambaran bagaimana juragan memeras pekerja yang mereka kuasai, Pramoedya juga telah menyebut satu kisah keberhasilan pembantu yang lepas dari cekaman juragannya. Seorang pelayan mampu menjadi orang bebas sebagai pekerja pabrik. Status sosialnya tidak banyak meningkat. Kondisinya sebagai pembantu rumah tangga tidak lebih dari perbudakan, tetapi sebagai pekerja pabrik dia menikmati hidup sebagai warga yang lepasan.
Lebih jauh lagi, narator telah memperhatikan bahwa kebebasannya yang baru telah memungkinkannya untuk bertemu dengan kelas pria yang lebih baik. Narator melihatnya berjalan dengan seorang pria berpendidikan yang memiliki sepeda Raleigh, simbol kemakmuran material bagi pekerja urban.
Menyimpulkan ceritanya, Pramoedya melalui narator menyadari bahwa para pelayan adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat “beradab dan berbudaya” Timur yang sering digambarkan dalam propaganda seniman dan politisi (MDR: 125). Orang cenderung lupa, (seperti juga dia), seberapa banyak hal tersebut dilebih-lebihkan sedemikian sehingga penggambaran adat-istiadat kesopanan, budi bahasa, dan perilaku berbudaya cenderung diidentifikasi dengan priyayi.
Orang cenderung menerima penggambaran seperti itu begitu saja, mereka lupa bahwa para pelayan yang memiliki adat istiadat dan etika yang berbeda dari priyayi pada kenyataannya juga merupakan bagian dari ras manusia yang beradab. Berdasarkan kisah ini, kita menemukan beberapa penajaman penting dalam pemahaman Pramoedya tentang masyarakat.
Pertama, pemahamannya mengenai kekuatan mobilitas sosial dimana beberapa majikan di masa sebelumnya juga sempat menjadi pelayan. Kedua, dia kini dapat melihat bahwa hak istimewa yang terus dinikmati oleh priyayi di masa sekarang berasal dari pemerasan. Ketiga, dia juga mampu melihat pembantu rumah tangga beraneka ragam, bukan berbeda dalam sifat dasar bawaan mereka sebagai pelayan, tetapi karena sifat dasar majikan mereka.
Pengarang telah mengaitkan kondisi “runyam” para pelayan dengan kondisi yang sama dari majikan mereka, karenanya Pramoedya pada saat penulisan cerita ini dapat melihat bila rangka sosial budaya “gusti-kawula” tidak selalu rukun dan bisa saja berlawanan dengan gambaran yang diproyeksikan dalam tradisi sastra Jawa. Keempat, dengan mengamati para pelayan itu terus-menerus, dia dapat melihat bahwa para pelayan juga merupakan bagian dari peradaban. Narator tidak dapat lagi mengabaikan keberadaan mereka.
Pada tahap ini Pramoedya melalui narator masih mengakui bahwa para pelayan memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda dengan priyayi. Namun, dia sekarang dapat melihat juga bila adat istiadat dan budaya priyayi itu tidak selalu adiluhung.
Pada saat yang sama dia sekarang mampu melihat bahwa nilai yang dianut para pekerja tidak selalu buruk. Yang lebih penting lagi, walau Pramoedya tidak setuju dengan unsur pemerasan yang tak terkendali di masyarakatnya, dia belum merasa cukup putus asa pada saat ini karena mampu membuat dirinya menggambarkan satu kisah sukses di tengah semua penderitaan yang dialami para pekerja rumah tangga tersebut.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa Pramoedya masih sangat yakin dengan reformasi yang tepat, masyarakatnya dapat diubah menjadi masyarakat yang ramah pada sesamanya.
Dikutip dengan seizin penerbit Komunitas Bambu dari buku Savitri Scherer, Pramoedya A.Toer: Dari Budaya ke Politik 1950-1965, hlm. 82-85. Bukunya tersedia di Tokopedia, BukaLapak, Shopee atau kontak langsung ke WA 081385430505