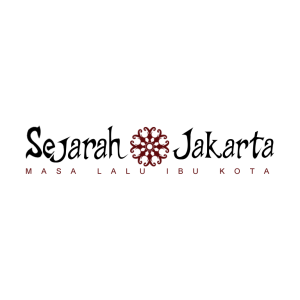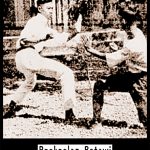Senen adalah pasar dan pasar dalam tradisi batak yang disebut onan merupakan pusat peristiwa-peristiwa penting. Sebab itu onan menjadi ruang kerakyatan dan tempat elite bergaul menimba inspirasi dan aspirasi, bahkan memulai revolusi.
Seorang janda mengumumkan siap dipinang kembali di onan, tandanya ia menaruh ranting beringin di sela rambutnya. Kehadiran seorang anggota marga baru diumumkan di onan. Bahkan lahirnya agama baru dimulai dan mengumumkan diri di onan, seperti agama Parbaringin. Termasuk perang Batak itu pun—menurut Lance Castles— bermula dari dirusaknya onan sebagai saka guru tertib hukum dan sistem politik Batak Toba.
Kerangka berpikir onan itulah yang dibawa Sitor Situmorang sebagai remaja 18 tahun anak kepala suku Batak saat pergi merantau ke Batavia untuk melanjutkan sekolah. Saat itu pertengahan Juli 1941, Sitor tiba di Batavia dan segera mencari onan. Sitor menemukannya di Pasar Senen. Secara konseptual konteks kultural-historisnya Pasar Senen setara dengan onan na marpatik atau pasar besar tertua di Limbong-Sagala, onan Simanggurguri.
Pasar Senen, kata Sitor dalam otobiografinya, adalah pusat kehidupan pelajar dan mahasiswa, tempat belanja dan berkencan. Sejak tahun 20-an para klepek sebutan untuk pelajar STOVIA memang kerap menjadikan Pasar Senen tempat rendezvous. Tidak aneh jika inspirasi bikin Konggres Pemuda yang sohor kemudian disebut Sumpah Pemuda pun kata Bahder Djohan muncul di Pasar Senen, saat para klepek STOVIA makan nasi goreng bersama Mohammad Hatta.
Baca Juga:
- Tempat-Tempat yang Diingat di Jakarta Pusat Dulu
- Dari Gerobak Kaset Keliling sampai Gelaran Lapak Underground
- Cililitan Punya Tuan Pieter van der Velde
Mohammad Yamin yang jadi motornya Konggres Pemuda itu hampir saben malem deprok di bawah lampu penerang jalan di Pasar Senen membaca buku-buku yang didapatnya dari loakan buku di sana.
Sebab itu tidak aneh jika pada Juli 1941 itu Sitor rela merogoh koceknya 15 gulden untuk dapat kost di Bungur, tidak jauh dari Pasar Senen. Di Bungur itu pula ia tinggal bertetangga dengan Parada Harahap, pimpinan koran nasionalis Bintang Timur yang saben pulang dari bersekolah di Salemba, cepat ia genjot sepedanya ke kantor koran itu di Senen agar bisa membaca di papan tempel khusus untuk bacaan umum.
Jepang datang dan sekolahnya Sitor kekandasan, tetapi ia tidak sedih sebab ia semakin yakin akan cita-citanya. Sitor ingin menjadi jurnalis nasionalis, persis Parada Harahap. Jurnalis yang berpengetahuan dan berkemanusiaan yang bahkan telah menjadi pimpinan media tidak berpihak kepada modal dan kekuasaan, tetapi kebenaran.
Sitor memang tidak jadi jurnalis di Pasar Senen, tetapi cita-cita itu tumbuh mekar di pasar yang lain, yaitu Pasar Sentral di Medan tempat berkantor koran republiken Waspada. Mohammad Said pimpinan Waspada menyebut Sitor sebagai mutiara terpendam di pedalaman revolusi Sumatera.
Said kemudian mengirim Sitor sebagai jurnalis ke Betawi lagi yang tak selang lama setelah proklamasi ditinggalkan pemerintahan Sukarno-Hatta ke Yogyakarta dan memasuki zaman “bersiap” yang artinya merdeka dan rela mati. Sekali lagi ia ke Pasar Senen sebab pusatnya “bersiap” itu di pasar Senen.
Sejarawan Robert Cribb bilang “bersiap itu” artinya revolusi. Sebab itu tidak salah jika ada Parnudya A. Toer bilang di pasar Senen itulah revolusi nasional dimulai. Bukan oleh para elite, tetapi wong cilik-nya, para bandit dan pelacurnya.
Bukankah poster penyemangat revolusi Boeng Ajo Boeng! yang diminta Sukarno digambar Affandi dan kata-katanya dari Chairil Anwar yang saben hari beroperasi di Pasar Senen serta—maaf—akrab dengan pelacur-pelacurnya yang saben-saben memanggil pelanggannya Boeng Ajo Boeng! Alangkah sedapnya revolusi dipicu kata ajakan pelacur Pasar Senen.
Sitor memang ke Yogyakarta dan mengalami revolusi. Bahkan ditangkap intel Belanda serta di penjara di Wirogunan. Tetapi, revolusi di pasar Senen itulah yang menginspirasinya untuk mulai berevolusi dari wartawan menjadi sastrawan.
Ada pengakuan dari Sitor bahwa ia menjadi penyair di Kaliurang, daerah dataran tinggi Jogjakarta. Namun, cobalah percaya penyair kadang suka pula berdusta. Salah satu dustanya Sitor soal hari lahirnya sebagai penyair itu.
Kalau buka buku kumpulan sajaknya yang 1068 halaman itu, sajak pertamanya Sitor itu “Pasar Senen”. Ia dalam empat sajak pertamanya merayakan pasar Senen. Merayakan “Aminah gadis tukang kopi dan si kebaya merah”, “doger dan pengemis kecil”, “anak rantau cari hiburan di gang sepi”, “nafas bahagia mabuk dada montok”.
Entahlah apakah Sitor juga seperti Chairil yang hidup di antara kopi, doger, pengemis dan pelacur? Sajaknya menjawab iya sebagai ruang kreatif. Begitu juga banyak mereka yang segenerasi dengan Sitor yang disebut kelompok Gelanggang Seniman Merdeka, yaitu Asrul, Pram, Rivai dll.
Itulah generasi yang kemudian disebut Seniman Senen dan pada 1970-an hilang serta ingin dihidupkan kembali oleh Bang Ali sebagai Gubernur Jakarta setelah membaca esei nostalgia Ajip Rosidi tentang Pasar Senen di Intisari. Kemudian jadilah TIM.
Pada 11 November 2015, ketika Irawan Karseno menyambut pidato kebudayaan Nirwan Arsuka, sebagai Ketua DKJ, ia mengeluhkan nasibnya TIM yang akan menyusul menyurut sebagaimana nasib sumber inspirasinya, pasar Senen. TIM sakratul maut (kalau tidak bisa disebut “mati”) karena salah kebijakan pemprov DKI Jakarta yang buta raison d’etre atau alasan keberadaannya.
Kini, Pasar Senen tetap pasar. Tetap besar tetapi dikerdilkan sehingga tinggal ruang besar yang hampa. Tiada lagi pasar Senen sebagai ruang kerakyatan tempat elite bergaul menimba inspirasi dan aspirasi. Suatu ruang penuh imajinasi telah tamat. Suatu medan revolusi telah berakhir, bahkan sisa-sisanya dimatikan di tengah kekuasaan Presiden Jokowi yang berusaha menghidupkan kembali revolusi—kata yang pernah lahir dan besar di pasar itu.

Revolusi hidup kembali digandengkan dengan persoalan-persoalan krisis nilai kejiwaan. Begitulah lahir “Revolusi Mental. Tetapi, apalah artinya revolusi tanpa inspirasi, aspirasi? Apalah artinya revolusi tanpa imajinasi? Dulu revolusi dimulai oleh rakyat, menjadikan rakyat sebagai unsur utamanya. Kini rakyat sampiran belaka.
Bahkan di Jakarta tempat Jokowi pernah menjadi gubernurnya dan kemudian diusung menjadi presiden dengan jargon Revolusi Mental—rakyat dan kampungnya digusur sambil dituduh sebagai maling, pencuri, bahkan antek komunis. Apakah artinya revolusi tanpa rakyat, tanpa sifat kiri, dan tanpa kampung?
Tetapi, sudahlah, tulisan ini tokh bukan untuk mengritik kekuasaan, tetapi memperingati kematian. Namun, sungguh kematian Sitor semakin mengakrabkan kita kepada hidupnya sebagai kawasan historis yang kaya dan dapat menjadi pintu merayakan suatu generasi perumus pertanyaan-pertanyaan besar sekaligus jawaban-jawaban persoalan keindonesiaan dan kebudayaan modern yang sejak proklamasi abai diurus negara.
Negara terlalu sibuk melihat pasar dunia, pasar internasional dan melupakan bahkan membunuh pasar rakyat, seperti pasar Senen yang kaya menawarkan inspirasi, aspirasi dan imajinasi bahkan kunci revolusi.
Dikutip dengan seizin penerbit Komunitas Bambu dari buku JJ Rizal, Sitor Situmorang Biografi Pendek, hlm. 119-121. Bukunya tersedia di Tokopedia, BukaLapak, Shopee atau kontak langsung ke WA 081385430505
Tulisan ini dibacakan pada acara “Pasar Senen, Sitor dan Harimau Tua” (Pertunjukan Instalasi Teks 1 Tahun Meninggalnya Sitor Situmorang), 20 Januari 2016 di Teater Kecil Taman Ismail Marjuki, pukul 19.30.